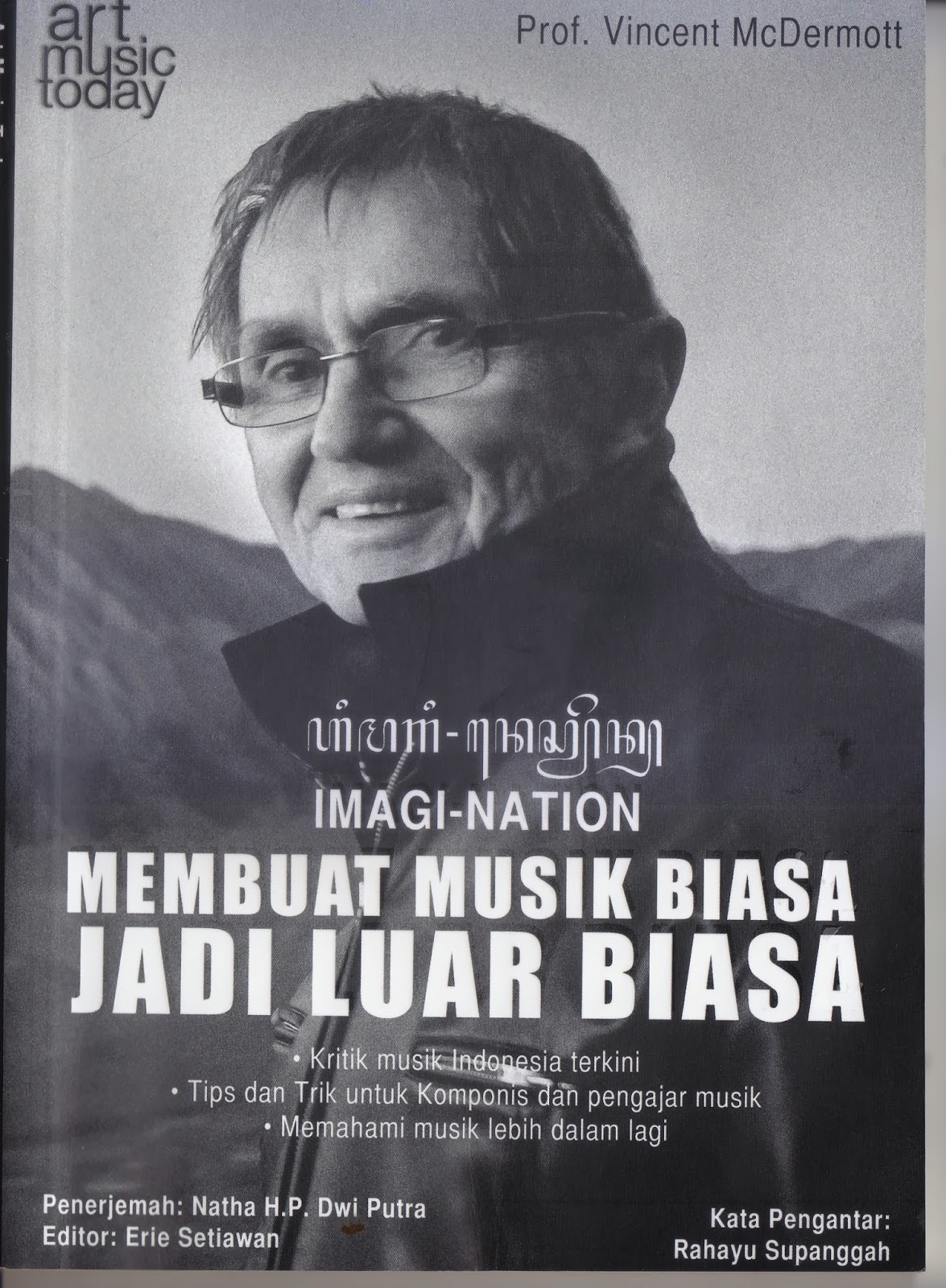Kisah Gong
Gamelan
Di Jawa, gong dalam perangkat gamelan
ageng menjadi instrumen paling besar. Bentuknya bulat berpencu. Gaung suaranya
menggema panjang. Gong menjadi penanda orkestrasi sebuah gending untuk dimulai
atau diakhiri. Bahkan masyarakat Jawa meyakini, gong tak sekadar alat musik, namun
sesak dengan pelbagai timbunan mitos. Dibanding dengan instrumen gamelan yang
lain, cara membuat gong tergolong lebih kompleks dan rumit. Sebelum gong dibuat,
para penempa (pande) harus melakukan ritual atau laku khusus seperti puasa,
semedi dan tirakat. Hal itu dilakukan agar mendapatkan hidayah berupa
keselamatan selama pembuatan gong. Terhindar dari bahaya semacam percikan api
di besalen. Serta gong buatannya menjadi lebih “ber-aura”. Gong diyakini
membawa peruntungan dan kisah tersendiri bagi masyarakat Jawa. Ia dianggap
sebagai “rumah” bagi para dewa dan arwah leluhur. Karenanya, banyak sesaji
dupa, kembang tujuh rupa dan kemenyan senantiasa diletakkan di dekat gong -bukan
pada instrumen yang lain-. Gong menjadi benda suci yang dikeramatnya. Ia
menjelma sebagai sang “Kyai” dan “Nyai”. Nama prestisius yang hanya diberikan
pada makhluk pembawa berkah dan pemberi kutuk. Lihatlah Kyai Macam Putih, Kyai
Surak,
Kyai Kumitir, Kyai Gerah Kapat, Kyai Muncar, Nyai Sepet Madu, Kyai Kanyut Mesem.
Kala perayaan Sekaten berlangsung di
Solo, ratusan orang “ngalap berkah” lewat gong Kyai Guntur Sari dan
Guntur Madu. Mereka memanjatkan doa, harapan dan membuka nadhar kehidupan. Hal
ini bukan berarti mereka menyembah gong. Peristiwa itu adalah wujud “negosiasi”
manusia Jawa kepada tuhannnya dengan meghadirkan gong sebagai modal. Gong
adalah “simbol” dunia kosmis, muara bertemunya bagi hamba dan gusti. Dalam
konteks musikalitas, gong menjadi puncak bunyi yang paling ditunggu. Gending
yang dibunyikan senantiasa memiliki beberapa siklus perutaran. Bunyi gong
berarti menandakan telah terlewatinya satu rangkaian gending secara utuh. Gong
menjadi “instrumen struktural” dalam karawitan Jawa. Kehadirannya membentuk
struktur gending, sama seperti kenong, ketuk dan kempul. Bunyi gong tidak serta
merta sesuai dengan ketukan (tempo dan ritme) gending. Justru sebaliknya, bunyi
gong yang indah adalah yang nggandul
atau terlambat dalam beberapa detik. Hal ini menjadi ciri estetik yang tipikial
bagi musik Jawa atau gamelan.
Dalam konteks sosial, gong menjadi
penanda bagi sebuah hajat agung untuk digelar. Lihatlah, sebelum acara besar dimulai,
senantiasa ditandai dengan pemukulan gong terlebih dahulu. Pemukul (penabuh)
gong bukanlah sebarang orang, namun tokoh penting yang diagungkan seperti
pejabat, presiden, gubernur dan lain sebagainya. Gong mengawali harapan baru untuk
kehidupan yang lebih baik. Dentum bunyi gong laksana untaian doa yang menggema.
Kehadiran gong menghiasi acara-acara besar di Indonesia. Namun sayang, hal itu
berbanding terbalik dengan nasib para pembuat gong. Pertaruhan nyawa dalam
membuat gong tak diimbangi dengan hasil atau pamrih yang disemai. Para pande
itu tetap hidup dalam kepungan kemiskinan, sementara hasil karyanya telah menggema
ke penjuru dunia. Hal ini yang oleh I Wayan Sadra (komponis) dijadikan sebagai
salah satu tema karyanya dengan judul Otot
Kawat Balung Wesi (2007). Sadra mencoba berkisah tentang kepedihan nasib para
pembuat gong.
Kerukuranan
Narasi kerukunan hidup di dunia juga
dimonumen dan disimbolkan lewat “Gong Perdamaian” yang dimonumenkan di beberapa
negara di antaranya Indonesia, Swiss, China dan Hungaria. Bentunya sama dengan
gong yang ada di Jawa, bulat berpencu. Gong kemudian dianggap sebagai alat musik
yang tak hanya mempresentasikan Jawa namun juga nusantara bahkan dunia.
Kisah-kisah tentang gong telah berpendar luas. Lihatlah masyarakat Dayak di
Kalimantan, gong menjadi simbol kehormatan sekaligus legitimasi atas kekuasaan
seseorang. Hanya kepala suku dan istri yang diperbolehkan duduk di atas gong.
Gong juga menjadi syarat bagi berlangsungnya ritual sakral seperti upacara
kematian pada mayarakat Dayak Banuaq (Joko Gombloh, 2009). Di Bali,
penghormatan terhadap gong diabadikan sebagai sebuah nama dari banyak perangkat
gamelan, seperti Gong Kebyar, Gong Gede dan Gong Semar Pagulingan. Di Sumatra
Barat gong juga dikenal dengan sebutan Talempong untuk upacara dan selebrasi
pesta. Bahkan gong juga ditemukan di banyak negara Asia seperti Thailand (gong
hui), Vietnam (cai thieu can), China (yun luo), Kamboja (kong thom), Filipina
(gangsa), Burma (kye vaing). Konon, gong dipercaya sebagai instrumen tertua
yang pernah dibuat manusia. Hal ini dapat ditelisik dalam pelbagai situs,
prasasti dan relief candi. Kehadiran instrumen berpencu itu terpahat jelas di setiap
pembabakan sejarah hidup manusia. Gong menjadi katalisator yang menghubungkan antar
satu kebudayaan dengan yang lain.
Bagi masyarakat di Jawa, dianggap tabu
jika dalam setiap pesta dan hajatan tak “nggantung
gong”, yang berarti ada kewajiban untuk menghadirkan klenengan
(gending-gending) gamelan. Namun sayang, kisah-kisah tentang gong itu telah
mengalami kebangkrutan eksistensi. Kita lupa menelisik gong sebagai simbol
perekat dan pemersatu antar etnis dan suku. Sebaran gong di Jawa dan di
nusantara bahkan dunia menunjukkan bahwa kita sejatinya adalah saudara, berasal
dari rumpun budaya yang tak jauh beda, tak ada yang lebih rendah dan tinggi di
antaranya. Kehadiran gong menjadi satir atas maraknya kerusuhan berbau rasial
yang dewasa ini sering terjadi. Kebertahanan gong hingga saat ini justru
mengingatkan kita tentang persentuhan mesra antar kebudayaan. Karenanya, tak
mengherankan kemudian jika gong dianggap mampu menjadi simbol perdamaian di
antara kita.
Aris Setiawan
Etnomusikolog, Pengajar
di Institut Seni Indonesia Surakarta